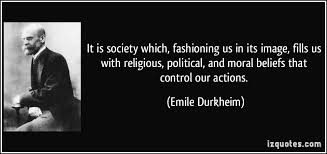Beberapa hari yang lalu salah satu karib bertanya pada saya via Whatsapp tentang apa saja diskusi yang sering muncul di salah satu grup saya. Pertanyaan ini agak aneh menurut saya. Alih-alih langsung menjawab pertanyaannya, saya justru bertanya kembali, mengapa ia mempertanyakan hal itu. Akhirnya berceritalah ia, beberapa hari ini grup WA-nya berdiskusi tentang tema sensitif, yakni perdebatan antara sunni-syi’ah. Dalam beberapa kali diskusi ia memiliki ro’yun yang berbeda dengan teman-temannya di grup tersebut. Tetapi dalam beberapa hari itu ia justru merasa terganggu dengan posisinya yang semakin terpojok karena gagasannya yang berbeda dari teman-temannya itu. Merasa cukup risih dan terganggu dengan diskusi panjang di media sosial itu, karib saya ini pun menenangkan dirinya sendiri dengan berkata, “mungkin memang –pendapat- saya yang salah, mungkin memang saya yang aneh, sehingga hanya saya yang berpendangan berbeda dari teman-teman yang lain”.

www.keepcalm-o-matic.co.uk
Inilah dunia kita saat ini, terhubung dan tanpa sekat lagi. Interaksi maya dapat terjalin -bahkan kalau perlu lebih dari- 24 jam. Saya pribadi termasuk orang yang tidak mudah untuk menegasikan diskusi-diskusi dan perdebatan di sosial media. Dan untuk secara kreatif dan arif menyikapinya, secara perlahan saya mencoba untuk tidak banyak berinteraksi di dalamnya. Dan di saat kita telah menjadi manusia di “desa global” ini, maka isu dan peristiwa apapun –mau-tidak-mau- menjadi santapan kita sehari-hari.
Santapan sehari-hari yang tiba-tiba datang dan menjadi kado pergantian tahun untuk umat Islam –salah satunya adalah- berita tentang eksekusi mati Sheikh Nimr al-Nimr, seorang dai sekaligus aktifis pro-demokrasi dari Provinsi Selatan (Provinsi dengan mayoritas Syiah di Kerajaan Arab Saudi, masyarakat disini sering mengeluhkan marjinalisasi dan ketidakadilan Pemerintah) yang cukup vokal dan dalam beberapa kali demonstrasinya kemudian dianggap oleh Pemerintah Arab Saudi sebagai teroris. Buat saya, kabar ini sebenarnya hanya pantulan kecil saja dari hatred yang akhir-akhir ini sering berdengung di sekitar kita. Jauh lebih menghujam daripada kabar ini adalah tulisan, status, potongan-potongan komentar di berbagai media sosial yang setiap hari dan setiap saat datang pada kita. Merefleksikan daily hatred imposing, ada dua hal yang menggelitik saya.

Sumber: http://www.theguardian.com
BIAS PEMBERITAAN
Pertama, pemberitaan tentang eksekusi mati Sheikh Nimr al-Nimr ini memiliki daya “radiasi kognisi” yang tajam terutama berkenaan dengan adanya konflik antar madzhab di dalam internal umat Islam. Sama seperti potensi-potensi konflik lainnya, gesekan antara dua unsur ketika dibaca melalui akar-akar primordialismenya, yang mencuat ke publik adalah kegagalan publik untuk membaca secara jernih persoalan mendasar dari gesekan tersebut. Kerusuhan yang terjadi antara masyarakat pribumi dengan masyarakat etnis Bugis di Kupang pada tahun 1999 sebenarnya adalah gesekan antara pedagang (yang kebetulan orang Bugis) dengan pembeli yang orang dari salah satu suku asli di NTT. Barangkali contoh yang lebih paralel dengan kejadian Syeikh Nirm al-Nimr adalah keberadaan Ustadz Tajul Muluk sebagai tokoh Syiah di Sampang, yang harus menerima putusan hakim sebagai provokator kerusuhan di Karanggayam Sampang tahun 2012.
Kembali pada berita tentang Syeikh Nimr Al-Nimr yang sebenarnya adalah tentang ketegangan antara Pemerintah dan rakyatnya, antara otoritas yang cenderung totaliter dan aktivis prodemokrasi menjadi bias, dan hanya bisa dibaca oleh sebagian dari umat Islam, melalui cara pandang primordial, sebagai perselisihan antara Sunni dan Syi’ah.
Perihnya adalah, ketika perselisihan itu menjadi diskursus dominan saat ini, maka radiasi kognisi tadi bekerja secara berlapis-lapis. Yakni kepada mereka yang tidak mampu melakukan bacaan kritis terhadap suatu berita, maka berlaku hukum “berita = kebenaran”.
KITA DAN BERITA
Kedua, sejalan dengan imbas dari radiasi kognisi di atas, ada paralelitas kelemahan antara cara menerima berita (news) dengan cara kita mencerna tulisan, postingan, status, dan potongan-potongan komentar di media sosial yang sehari-hari berdatangan pada kita. Dalam prosesnya, postingan yang datang dan masuk ke lini terdekat dari kognisi kita secara langsung menekan kita untuk larut dan ikut menyetujuinya tanpa menyisakan ruang untuk melakukan kritisisme terhadapnya. Ditambah lagi daya kerja media sosial yang bersifat interaktif akan semakin mudah menebalkan dominasi dari suatu diskursus, maka ruang kritisisme semakin menjadi barang langka. Tidak heran bila, misalnya, karib saya tadi merasa terpinggirkan, merasa dirinya aneh, dan bahkan merasa dirinya salah, saat pendapatnya tentang perdebatan teologis sunni-syi’i berbeda dengan kawan lainnya. Karena sifat media sosial dan dunia maya itu melakukan akumulasi terhadap segala gagasan yang –secara kuantitatif- lebih sering muncul. Atau dalam bahasa saya, ya pendapat dan gagasan yang mendominasi.
Dalam kondisi seperti ini, pikiran kita akan cenderung terdorong untuk ikut menjawab/berkomentar/bersuara “YES or NO” dalam kasus teman saya, ia harus memilih be “SUNNI or SYI’I”. Padahal persoalan pentingnya, lagi-lagi menurut saya, bukan pada menjawab soal either or seperti itu. Tetapi bagaimana anda memandang persoalan itu secara lebih luas, hubungannya dengan persoalan-persoalan yang lain, serta signifikansi persoalan tersebut di era saat ini.
Terakhir, tentu saja tulisan ini bukanlah –sama sekali- memilih menjadi supporter bagi SUNNI atau SYI’I. Karenanya bila tulisan ini masih di-copy paste, disebarkan, di-share, apalagi sampai dituduh sebagai supporter salah satu dari keduanya, “mungkin anda perlu meninggalkan tulisan ini, dan pergilah piknik!”
Untuk Yulia, di Filsafat UGM.